Dasar Monyet
TULISAN ini hendak dibuka dan diakhiri dengan nalar kurangajar. Berhentilah memaki seseorang dengan menyebut penghuni kebun binatang karena makian itu menghina sampai jauh ke orangtua yang bersangkutan. Berkata ‘dasar monyet’ kepada seseorang, misalnya, samalah mengatakan ayah dan ibunya monyet sebab belum pernah ada emak dan bapaknya monyet melahirkan anak bukan monyet, melainkan manusia. Monyet beranak monyet!
Demikianlah, orangtua yang tiada terkait dengan konteks persoalan terkena pula makian. Terjadilah dua perkara kurang ajar. Pertama, menyebut seseorang monyet. Kedua, secara tidak langsung memonyetkan orangtuanya. Jadi, berhentilah memaki bermonyet-monyet. Kita pun mestinya berhenti memaki-maki penyelenggara negara. Sekalipun saya belum pernah mendengar di ruang publik, DPR (misalnya) dimaki sebagai monyet, sebaiknya kita berhenti memaki DPR. Tentu, bertepuk tidak sebelah tangan, kecuali bermaksud menepuk angin.
Salah satu faktor utama untuk berhenti memaki DPR ialah DPR berhenti memperlakukan rakyat sebagai sekrup, apalagi sebagai monyet. Rakyat bukan sekrup, mestinya menjadi pegangan hakiki bagi siapa pun yang berkuasa. Apabila DPR menganggap rakyat sekrup, dengan analogi yang sama, anggota DPR merupakan wakil sekrup. Kalau DPR memperlakukan rakyat bak monyet, yang bahagia diberi kacang ketika reses dan kampanye, sesungguhnya anggota DPR memang menjadikan dirinya sendiri pun wakil monyet, yang nilainya pun kacangan.
Serupa halnya bila pemerintah menganggap rakyat sekrup; mereka pun pemerintahan sekrup. Kalau menteri menganggap rakyat monyet, dia pun menteri monyet. Padahal monyet tak perlu kabinet, tak perlu menteri, tak pula perlu presiden. Namanya juga monyet. Dalam pemilu, rakyat bukan sekrup, berapa pun harganya, apalagi seharga kacang. Dalam pemilu legislatif, partai ialah peserta pemilu. Akan tetapi, hak suara bukan hak konstitusional partai, melainkan hak konstitusional warga sebagai person.
Dalam relasi institusional dan personal, yang institusional itu ialah peserta pemilu (partai), penyelenggara pemilu (KPU), pengawas pemilu (Bawaslu), dan pengadil pemilu (MK). Dalam pilpres, partai bahkan hanya pengusung, bukan peserta pemilu. Yang punya hak suara, yang menentukan, ya rakyat. Akan tetapi, setelah pemilu usai, produk pemilu yang dihasilkan, apakah itu lembaga legislatif maupun eksekutif, mereka menarik otonomi hak personal konstitusional dari rakyat menjadi sepenuhnya milik mereka.
Kekuasaan itu amanah, ternyata dipakai sesukanya, bahkan memperlakukan rakyat yang punya hak konstitusional personal itu sebagai sekrup. Bahkan, bak monyet yang cukup diberi kacang. Contohnya, apakah DPR dan pemerintah bertanya, rakyat lebih memilih sistem terbuka atau tertutup, suara terbanyak atau nomor urut, dalam penentuan pileg? Inisiatif siapa pun, pemerintah atau DPR, tiap 5 tahun bongkar pasang undang-undang pemilu, tidakkah hal itu lebih menunjukkan ekspresi kegelisahan elite puncak partai yang khawatir tidak mendapat suara terbanyak dalam pileg, karena memang rakyat tidak percaya lagi, karena memperlakukan rakyat sekrup, bahkan monyet? Saya ingin mengajak, marilah kita berhenti memaki pemerintah atau parlemen. Sebaliknya, yang berkuasa, berhentilah memperlakukan rakyat sebagai sekrup. Apalagi mengatakan, ‘dasar monyet’, kepada siapa pun. Tidak hanya karena saya bersimpati kepada monyet asli, yang dinilai lebih rendah, tetapi lebih karena demokrasi memerlukan kritik daripada makian.

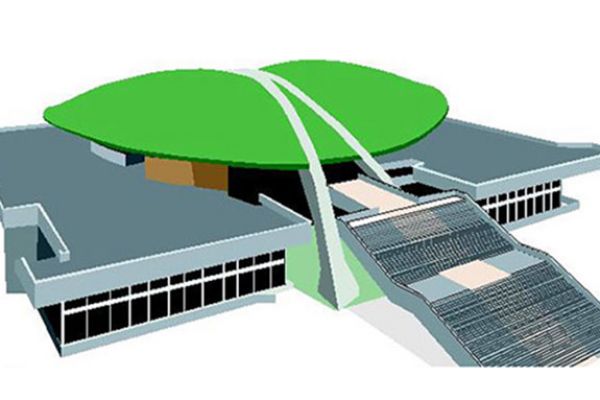
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.