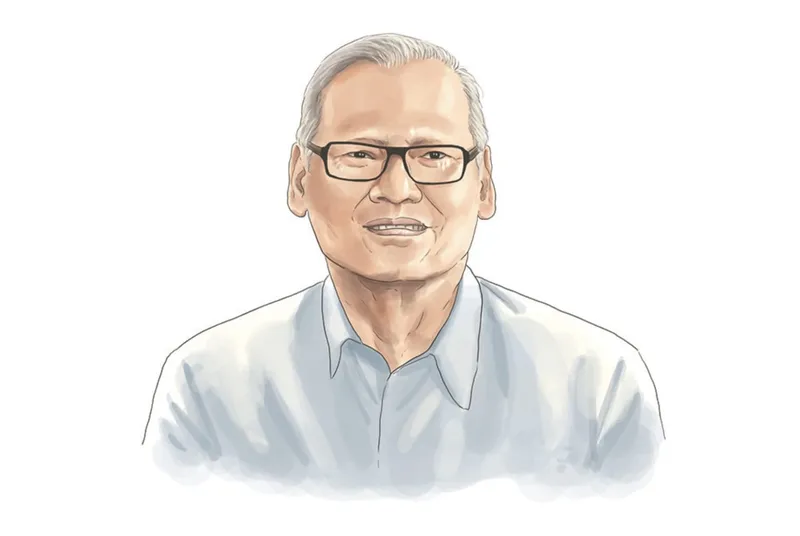Referendum untuk Pilkada
KIRANYA merupakan perkara buruk dalam kehidupan bertata negara jikalau pembentuk undang-undang mbalelo terhadap putusan pengawal konstitusi.
Ada tanda-tanda dalam hal pilkada, DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang bakal berselisih paham dan pengertian dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi.
MK menetapkan makna ‘dipilih secara demokratis‘ dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dipilih langsung oleh rakyat. MK pun terang benderang menyatakan, tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pilkada. Kendati demikian, mulai kencang suara partai-partai di DPR yang juga berkoalisi di kabinet, memaknai ‘dipilih secara demokratis’ itu adalah dipilih melalui lembaga perwakilan (DPRD).
Bila terjadi perselisihan mendasar dua lembaga negara legislatif dan yudikatif, Prof Saiful Mujani melalui akun media sosialnya berpendapat agar perselisihan mengenai pilkada itu diselesaikan oleh rakyat — melalui referendum. Tanyalah rakyat, manakah yang mereka setujui? Kepala daerah dipilih rakyat atau dipilih DPRD?
Saiful Mujani adalah ilmuwan politik pertama di luar Amerika Serikat yang dianugerahi penghargaan prestisius Franklin L Burdette/Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science Association (APSA).
Referendum itu pilihan agar pembentuk undang-undang tidak melanggar undang-undang karena tidak mengindahkan putusan MK. Akan tetapi, DPR dan pemerintah punya keyakinan sendiri perihal yang baik dan benar bagi negara ini — sekalipun itu tidak mengindahkan putusan MK.
Di antara dua ‘kebenaran‘ itu, siapa yang harus didengarkan? Siapa yang harus diikuti? Jawabnya bukan pembentuk undang-undang, bukan pula pengawal konstitusi. Bukan keduanya. Siapa? Rakyat. Melalui apa? Referendum.
Kiranya perlu diingatkan, dampak ketatanegaraan, bila DPR berkecenderungan dalam banyak perkara, tidak menghormati putusan MK. Terutama mengingat kedudukan MK dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Kata konstitusi, DPR ‘hanya dapat’ menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR, ‘setelah MK memutuskan’ bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Frasa ‘hanya dapat… setelah MK memutuskan…’ di dalam konstitusi itu, hanya punya satu makna, yakni DPR, untuk bersidang paripurna, harus menunggu putusan MK.
Terbiasa tidak menjalankan putusan MK dapat menggerus wibawa dan kredibilitas MK yang berwenang ‘memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum’.
Demikianlah, kedudukan MK dalam pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden itu sangat tinggi dan sakral. ‘Sakral‘ agar DPR yang juga berada di dalam MPR, tak sesukanya menjatuhkan Presiden RI — seperti sebelum reformasi.
MK adalah buah reformasi. DPR haruslah menghindari penggerusan wibawa MK. Kiranya cukuplah sudah upaya DPR mengendalikan MK melalui posisi politik pengajuan hakim konstitusi. Bahwa di dalam memutuskan judicial review, tiga orang hakim konstitusi yang diajukan DPR haruslah membela undang-undang hasil inisiatif DPR. Bila tidak, akan di-Aswanto-kan, sekalipun ini melanggar undang-undang.
DPR esensinya memang berada di ranah politik. Kata Hannah Arendt, “Setahu saya, tidak ada seorang pun yang pernah menganggap kejujuran sebagai salah satu kebajikan politik.”
Setahu Anda, apakah pernah ada yang menganggap referendum sebagai sarana legitimasi kebohongan rakyat? Memindahkan pilkada ke dalam kekuasaan DPRD adalah mencabut hak rakyat memilih langsung kepala daerah. Karena itu, referendum layak ditimbang kebajikan dan kearifannya.